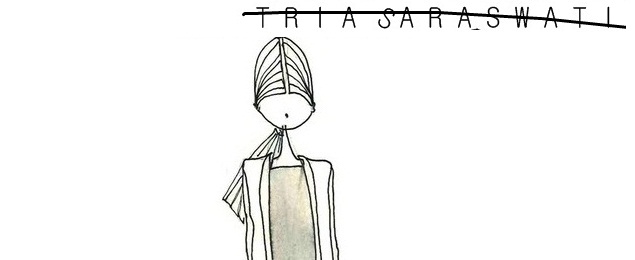Dengan bermodal keberanian,
catatan kesehatan yang cukup baik dan hanya Sabtu-Minggu bisa terlepas dari urusan kantor, saya pun memberanikan diri untuk mendaki ke Gunung Pangrango, gunung
yang baru saya tahu namanya dua minggu sebelum hari H.
Pendakian pertama, yang saya
inginkan hanyalah kejutan dari semesta. Saya tidak mencari tahu bagaimana medan
dan pemandangan selama mendaki nanti. Yang saya lakukan adalah mempersiapkan diri. Persiapan diri yang saya maksud adalah
menjauh dari dunia modern, setidaknya dalam 1 minggu sebelum berangkat saya puasa
apapun kegiatan manusia zaman ini, seperti Social Media dan Mall. Tidak
berjalan sempurna karena pekerjaan saya ada di Social Media, ya setidaknya saya
tidak membuka akun pribadi saya. Ibarat tradisi pemutihan menjelang menikah. Saya ingin mendaki dalam keadaan suci. Suci dari segala dunia zaman sekarang yang jauh dari kesadaran tentang alam. Beberapa teman tidak mengerti mengapa saya melakukan ini dan malah mencemooh. Biarlah.
Saya juga tidak berekspektasi apapun dengan pendakian ini. Tidak menghayal sedikit pun tentang apa yang kira-kira terjadi saat pendakian nanti.
Saya juga tidak berekspektasi apapun dengan pendakian ini. Tidak menghayal sedikit pun tentang apa yang kira-kira terjadi saat pendakian nanti.
Perasaan menjelang mendaki
seperti mual yang terjadi di otak. Perasaan itu memuncak ketika pesan dari tour
untuk meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Hal yang tidak mungkin saya lakukan kepada
Ibu yang selalu mengedepankan kecemasan. Wajar memang bila seorang Ibu melarang
anak perempuannya untuk mendaki gunung. Akhirnya saya memilih untuk berdoa,
untuk tidak terjadi seseuatu yang bisa membuat saya menyesal karena tidak meminta izin
orang tua terlebih dahulu.
Jumat, 6 September 2013, seperti
Jumat malam pada umumnya, macet. Saya sampai ke Depok pukul 20.30, sedangkan
jam 22.00 saya harus berada di Terminal Kampung Rambutan. Salah saya tidak
belajar dari pengalaman, saya selalu menyepelekan urusan packing. Baru saya
lakukan 15 menit sebelum keluar dari kamar. Akhirnya banyak barang yang
seharusnya saya bawa tapi tidak terbawa, dan sebaliknya.
Pukul 21.30 saya sampai ke
Terminal Kampung Rambutan, mengubah alter ego menjadi Tria yang terpaksa acuh
dengan orang baru.
Singkat cerita, saya sampai
sekitar pukul 2 dini hari di Cibodas. Tidak memanfaatkan waktu untuk tidur,
saya malah duduk menyantap kopi bersama bapak-bapak sambil menonton
pertandingan Sepak Bola Belanda.
Pukul 4 pagi, pendakian dimulai.
Seluruh doa saya ucapkan berulang-ulang.
Kecemasan dan kegirangan saya redakan, keberanian saya bulatkan. Masih
gelap, wejangan-wejangan yang saya dengar sebelumnya saya patuhi, saya tidak
sekalipun menyorotkan senter ke kanan dan kiri.
Setengah jam pertama pendakian
nafas saya sudah tersengal-sengal. Bernafas melalui mulut, saya memang belum
bisa menyelaraskan nafas dengan gerakan yang semakin lama semakin menanjak
dengan medan batu-batuan yang tidak tentu tingginya.
Sempat ada monolog penyesalan.
" Mendaki Gunung? Lupa kalau pernah pingsan di kereta dan bis atau ketika Gladiresik Wisuda?”
“Itu beda,
pingsan karena kehabisan nafas bukan karena kecapekan”
“Kehabisan nafas atau
tidak sarapan?”
Saya teringat lagi satu wejangan
untuk tidak melamun sembarangan di hutan.
Ada perasaan malu untuk mengajak
orang disebelah saya untuk istirahat, saya tidak ingin terlihat lemah di mata
orang lain. Terlebih lagi mereka semua rata-rata sudah memiliki pengalaman
mendaki sebelumnya. Saya tidak ingin merepotkan orang lain, perasaan yang
seharusnya tidak ada saat itu. Saya
tertinggal oleh teman setenda saya, lalu berkenalan dan mendaki beriringan dengan
kelompok tenda lain, mereka adalah Surya, Yuda, Firman, Vita dan Lily.
Sampai akhirnya kami singgah
disepetak tempat beralas jembatan batu ditengah hutan untuk menunaikan ibadah
Sholat Subuh. Pengalaman sholat subuh yang mungkin akan saya ceritakan sampai
ke cicit saya. Udara dingin hingga ketulang, suara aliran air yang tenang,
kicauan burung, hembusan angin pada daun-daun dan bintang-bintang yang bertabur
berantakan di langit hitam. Letih dan cemas hilang seketika, perasaan bahagia
yang pernah saya rasakan ketika menonton Konser Sigur Ros terulang kembali.
Bersyukur, sangat bersyukur.
Satu penyesalan dan keberuntungan
yang saya yakinkan saat itu. Menyesal karena memaksa untuk membawa Carrier Bag
yang belum diisi saja sudah terasa berat, terlebih lagi saya punya catatan
buruk untuk kesehatan tulang punggung. Saya berjanji untuk hanya membawa Day
Pack saja untuk pendakian selanjutnya. Merasa beruntung karena menggunakan
celana gunung selutut, sebelumnya saya meragu karena takut kedinginan, tersayat
semak-semak atau dihinggapi lintah. Tadinya ingin menggunakan Skinny Jeans saja.
Untunglah kali ini saya melakukan pilihan yang tepat. Langkah kaki yang makin
lama meninggi pasti akan terasa menyiksa bila dipadukan dengan Skinny Jeans.
Matahari pagi adalah jaket paling
hangat yang saya temui disana.
Senter mulai disimpan, kupluk dan
sarung tangan saya selipkan diantara kantong celana,resleting jaket saya buka
dan syal mulai saya regangkan. Pernapasan saya makin lama, makin teratur. Mata
saya mulai meliar, mencari-cari sesuatu yang sekiranya dapat saya bawa pulang
ceritanya. Penglihatan saya merekam sekeliling, hutan, jurang, batu-batuan
sesekali melihat burung yang mengintip dari kejauhan. Sesekali merogoh kantong
untuk mendapatkan roti untuk sarapan dan handphone untuk memotret dan merekam.
Semakin menanjak, maka semakin sering pula saya dan teman-teman duduk
berselonjor. Hukum pendaki tak tertulis adalah menyapa dan memberi semangat
sesama pendaki, seperti “permisi Mas/Mba” “Duluan ya Mas/Mba”, atau “Yuk yuk
semangat”, hal-hal ramah seperti itu sebenarnya sangat bukan diri saya. Tapi
entah mengapa disana saya merasa tidak kaku melakukannya, semua seperti teman
lama, reuni dengan orang-orang tidak pernah saya temui.
 |
| Dari sudut pandang saya yang sedang tergolek ditepi trek karena kelelahan |
 |
| Saya ditengah pendakian |
Melangkah lebar untuk naik dataran yang lebih tinggi (bahkan ada yang setinggi lutut) makin sering saya temui selepas pukul 9 pagi. Saya mengurangi gerakan mendongak dan memperbanyak gerakan menunduk. Kenapa? karena ketika mendongak saya akan menyadari jalanan di depan saya semakin menanjak, rasa lelah akan datang sebelum saya mendakinya. Lebih baik saya menunduk dan tidak menyadari bahwa dakian semakian tinggi.
Sampai akhirnya, pemandangan tak
lagi hanya seputar hutan dan jurang, namun aliran air panas yang menciptakan kebulan asap putih. Cukup sulit
mendeskripsikannya tapi akan saya coba: Posisinya ada di tepi jurang, pijakan
hanya cukup untuk satu orang, pijakan ini bukan tanah melainkan batu-batu
sebesar telapak kaki yang dialiri air hangat yang mengalir dari dinding tebing.
Pilihannya adalah bila berpijak pada batu berisiko tergelincir karena licin,
bila berpijak pada air, sepatu akan basah sehingga langkah terasa lebih berat.
Saya pun mulai meniti jalanan itu, tangan kanan menyentuh permukaan gunung,
menggengam akar-akar yang ada, tangan kiri menyentuh kabel yang melintang
membatasi antara jurang dan dataran. Jangan tantang saya untuk berjalan sambil
melihat kebawah. Sesekali saya berpijak pada batu yang salah, batu yang rentan
berubah posisi ketika diinjak dan akhirnya terpaksa saya menenggelamkan kaki
pada air hangat. Titian ini memerlukan waktu setidaknya 5 menit, selama itu
pula suara hati tak henti-hentinya melantunkan doa.
 |
| Terlihat dari jauh uap dari muara air panas |
 |
| Saya, Yuda dan Vita di pangkal rute titian air panas. Perhatikan daratannya, itu bentuk nyata dari tulisan saya sebelumnya. |
 |
| Kandang Badak |
 |
| Kandang Badak dan para pendaki yang beristirahat |
Setelah Dzuhur, pendakian sesungguhnya dimulai. Tak lagi berpijak pada bebatuan dan beriringan dengan teman. Jalan setapak dengan pohon-pohon melintang, salah satu teman baru saya yang dipanggil Pocong menamai medan ini dengan ‘Jalan Kacau’. Saya perlu melompati, menunduk bahkan merangkak pada pohon-pohon yang melintang. Saya menyenangi jalanan seperti ini, seperti wahana-wahana hiburan yang kreatif dibuat langsung oleh Sang Pencipta untuk saya tanpa ada tangan manusia. Saya membayangkan diri saya sedang berada di suatu game, setiap saya melewati pohon-pohon itu dengan sempurna saya akan mendapatkan bonus poin atau combo untuk pohon-pohon yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Betapa beruntungnya saya dapat merasakan itu.
 |
| Persimpangan Gn Gede Dan Gn Pangrango |
 |
| Tanda ini yang menjadi acuan |
 |
| Yuda, Lily, Vina, Ipank, Agustina, Jimeng, Pocong, James, Ule, Saya, Lili, Surya |
Makin lama saya tidak lagi berjalan, namun memanjat. Untunglah saya ditemani teman-teman dan green ranger
yang membantu saya memanjat dataran itu. Perlu menarik nafas dalam-dalam
sebelum memanjat dataran setinggi dagu saya. Tanahnya basah, tentu tidak bisa
berpijak pada ujung-ujung tanah ketika memanjat. Pijakan hanya batu atau akar,
bila beruntung pijakan dapat sebesar setengah telapak kaki. Kalau tidak, saya
harus pintar melekatkan telapak kaki pada permukaan yang lembab dan merelakan
pergelangan pangkal tangan sakit karena ditarik oleh teman yang membantu saya. Medan
seperti itu berlangsung hingga menuju puncak, diselingi dengan medan yang
sangat lembab yang sebenarnya adalah tempat air mengalir. Salah satu Green
Ranger saya lupa Mas Widi atau Mas James menamai medan ini dengan “Jalur
selokan”, karena memang seperti selokan. Bila melewati medan ini, betis saya
harus rela kotor karena tanah liat.
Saya mulai sering berhenti untuk
istirahat dengan medan memanjat seperti ini. Pada suatu pemberhentian Mas Widi
berkata “Ini pendakian pertama ya? Hebat loh langsung pilih Gunung Pangrango!” dari
pernyataan itu bisa disimpulkan bahwa medan Gunung Pangrango ini tergolong
level yang tinggi. Dan hebatnya saya menempatkan Gunung Pangrango untuk daftar
pendakian pertama. Menurut Mas Widi, Pangrango medannya lebih susah
dibandingkan Mahameru.
Carrier Bag tentunya makin terasa
lebih berat, untunglah Mas James berbaik hati menawarkan bantuan untuk
membawakan Carrier Bag saya. Langkah saya menjadi lebih lincah untuk mencapai
Puncak Pangrango.
Sampai akhirnya.... Puncak
Pangrango! Saya, Tria Saraswati berusia 21 tahun 9 bulan, berhasil mencapai
puncak Pangrango 3019mdpl! Senyum mengembang tiada henti di pipi ini. Rasa
capek terbayar lunas dengan rasa haru dan bangga.
 |
| Puncak Pangrango, 3019mdpl |
 |
| Awan-awan dari Puncak Pangrango |
Bukan Puncak Pangrango tempat
peristirahat kita, tapi Mandalawangi. Mandalawangi adalah alun-alun Gunung
Pangrango, disana lebih indah. Dari Puncak Pangrango saya berjalan menurun
sekitar 7-10menit untuk menuju Pangrango. Ketika saya menyadari Mandalawangi
semakin dekat, saya berhenti sejenak untuk memasang earphone dan memutar
lagu Sigur Ros Hoppipolla. Menarik nafas dalam-dalam lalu mengerluarkannya
lewat mulut. Saya sudah siap dengan sejuta kejutan dari Mandalawangi diiringi lagu
Hoppipolla. Langkah per langkah makin terasa ringan menyadari Mandalawangi
hanya tinggal hitungan detik lagi.
Dan. Tepat pada bagian reff
Hoppipolla... Mandalawangi.
Sunset di Mandalawangi.
Hamparan dataran luas dengan
ribuan edelwies dengan langit senja membentang bersama awan yang bergerak lebih
cepat dari yang pernah saya temui seumur hidup. Matahari hangat. Mata tidak
rela berkedip. Mandalawangi berhasil menghisap rasa letih saya dengan
keindahannya. Saya sangat syukur bisa menyaksikan pertunjukan ini. Saya kembali
Individualis, saya mendengar ada yang memanggil namun saya abaikan. Saya ingin
mencumbu Mandalawangi, hanya antara saya dan Mandalawangi.
Seperti rumah
Seperti terlahir kembali
Seperti kualitas hidupku meningkat
Seperti cinta yang terbalas
Seperti hanya aku orang yang
paling beruntung di dunia
***
Tenda dipasang diantara dua pohon yang saya tidak tahu namanya, yang saya tahu ada Edelwies di kiri kanan halaman tenda saya. Lagi-lagi saya di bantu Mas James. Dingin benar-benar diluar dari prediksi saya, menyesel telah mengeluarkan sweater dari carrier bag ketika masih di kostan. Dingin menusuk ketulang, saya sempat berpikir saya bisa saja mati karena kedinginan. Saya dan teman setenda menyalakan api unggu kecil (karena dilarang untuk menyalakan api unggun besar takut mengakibatkan kebakaran hutan). Unggunan api itu tidak terlalu membatu, andai api bisa digenggam.
Jangan tanya indahnya bentangan langit saat itu. Bintangnya lebih dari kata indah.
Saya tidur lebih awal dari rencana yang saya susun, akumulasi dari kurang tidur, letih dan tidak tahan lama-lama diluar tenda. Kerap kali saya terjaga karena kedinginanan, sleeping bag rasanya hanya seperti helaian kain sifon. Akhirnya saya menyerah, pukul lima dini hari saya tidak lagi mencoba melanjutkan tidur. Keluar tenda untuk sholat subuh, lalu kembali menyalakan api untuk menghangatkan diri. Beruntunglah saya pertunjukan bintang saat itu belum usai. Mata saya menguasai seluruh bintang, mata-mata yang lain sedang tertutup di dalam tenda.
Matahari kian menampakkan diri, saya mandi dengan sinar matahari Mandalawangi. Setelah packing dan membungkus tenda saya berjalan menuju pusat Mandalawangi. Dengan berbantal Carrier Bag saya tidur ditengah sana. Mulai mencumbu Mandalawangi kembali. Memuaskan nafsu mata, karena sadar saya tidak mungkin mendapatkan pemandangan seperti ini di Jakarta. Ibarat di komik, mata saya memancar bunga-bunga semanggi berdaun empat serta titik-titik cahaya.
Setelah puas mengabadikan moment-moment bersama teman baru, kami pun mulai turun gunun
g. Perjalanan menurun juga tidak kalah seru, permukaan yang sebelumnya saya tempuh dengan cara memanjat kini dilakukan dengan merosot. Pantat terseret-tersendat di tanah-tanah lembab. Saya juga sempat singgah di suatu pos untuk merendamkan kaki di aliran air hangat.
Waktu tempuh turun gunung lebih cepat dari prediksi green ranger. Mereka memperkirakan kami semua akan turun jam 8 malam, namun kenyataannya jam 5 sore kami sudah sampai di Cibodas.
Dan kemudian masing-masing kembali ke peraduannya, berpisah.
Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Memberi banyak pelajaran dan mengingatkan saya untuk tidak henti bersyukur kepada Sang Pencipta. Salah satunya dengan keberadaan matahari, kini saya tidak lagi mengeluh tentang panasnya Jakarta, karena pernah mengalami suatu kondisi dimana saya memohon kepada Tuhan untuk membuka awan agar Matahari dapat menghangatkan saya.
Terima kasih atas perjalanan spiritual ini, Tuhan :)
 |
| Mandalawangi |
 |
| Hamparan Edelwies di Mandalawangi |
 |
| Matahari tenggelam di Mandalawangi |
 |
| Saya dikelilingi Edelwies |
Tenda dipasang diantara dua pohon yang saya tidak tahu namanya, yang saya tahu ada Edelwies di kiri kanan halaman tenda saya. Lagi-lagi saya di bantu Mas James. Dingin benar-benar diluar dari prediksi saya, menyesel telah mengeluarkan sweater dari carrier bag ketika masih di kostan. Dingin menusuk ketulang, saya sempat berpikir saya bisa saja mati karena kedinginan. Saya dan teman setenda menyalakan api unggu kecil (karena dilarang untuk menyalakan api unggun besar takut mengakibatkan kebakaran hutan). Unggunan api itu tidak terlalu membatu, andai api bisa digenggam.
Jangan tanya indahnya bentangan langit saat itu. Bintangnya lebih dari kata indah.
Saya tidur lebih awal dari rencana yang saya susun, akumulasi dari kurang tidur, letih dan tidak tahan lama-lama diluar tenda. Kerap kali saya terjaga karena kedinginanan, sleeping bag rasanya hanya seperti helaian kain sifon. Akhirnya saya menyerah, pukul lima dini hari saya tidak lagi mencoba melanjutkan tidur. Keluar tenda untuk sholat subuh, lalu kembali menyalakan api untuk menghangatkan diri. Beruntunglah saya pertunjukan bintang saat itu belum usai. Mata saya menguasai seluruh bintang, mata-mata yang lain sedang tertutup di dalam tenda.
Matahari kian menampakkan diri, saya mandi dengan sinar matahari Mandalawangi. Setelah packing dan membungkus tenda saya berjalan menuju pusat Mandalawangi. Dengan berbantal Carrier Bag saya tidur ditengah sana. Mulai mencumbu Mandalawangi kembali. Memuaskan nafsu mata, karena sadar saya tidak mungkin mendapatkan pemandangan seperti ini di Jakarta. Ibarat di komik, mata saya memancar bunga-bunga semanggi berdaun empat serta titik-titik cahaya.
 |
| Catur, Firman, Saya, Surya dan Yuda |
 |
| Saya dan Yuda |
 |
| Lily dan Saya |
 |
| Firman dan Saya |
 |
| Ule, Mega dan Saya |
 |
| Mas Widi, Lily, Saya dan Mas James |
 |
| Semua |
 |
| Saya dengan Vrksasana Pose di Mandalawangi |
Setelah puas mengabadikan moment-moment bersama teman baru, kami pun mulai turun gunun
g. Perjalanan menurun juga tidak kalah seru, permukaan yang sebelumnya saya tempuh dengan cara memanjat kini dilakukan dengan merosot. Pantat terseret-tersendat di tanah-tanah lembab. Saya juga sempat singgah di suatu pos untuk merendamkan kaki di aliran air hangat.
Waktu tempuh turun gunung lebih cepat dari prediksi green ranger. Mereka memperkirakan kami semua akan turun jam 8 malam, namun kenyataannya jam 5 sore kami sudah sampai di Cibodas.
Dan kemudian masing-masing kembali ke peraduannya, berpisah.
Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Memberi banyak pelajaran dan mengingatkan saya untuk tidak henti bersyukur kepada Sang Pencipta. Salah satunya dengan keberadaan matahari, kini saya tidak lagi mengeluh tentang panasnya Jakarta, karena pernah mengalami suatu kondisi dimana saya memohon kepada Tuhan untuk membuka awan agar Matahari dapat menghangatkan saya.
Terima kasih atas perjalanan spiritual ini, Tuhan :)